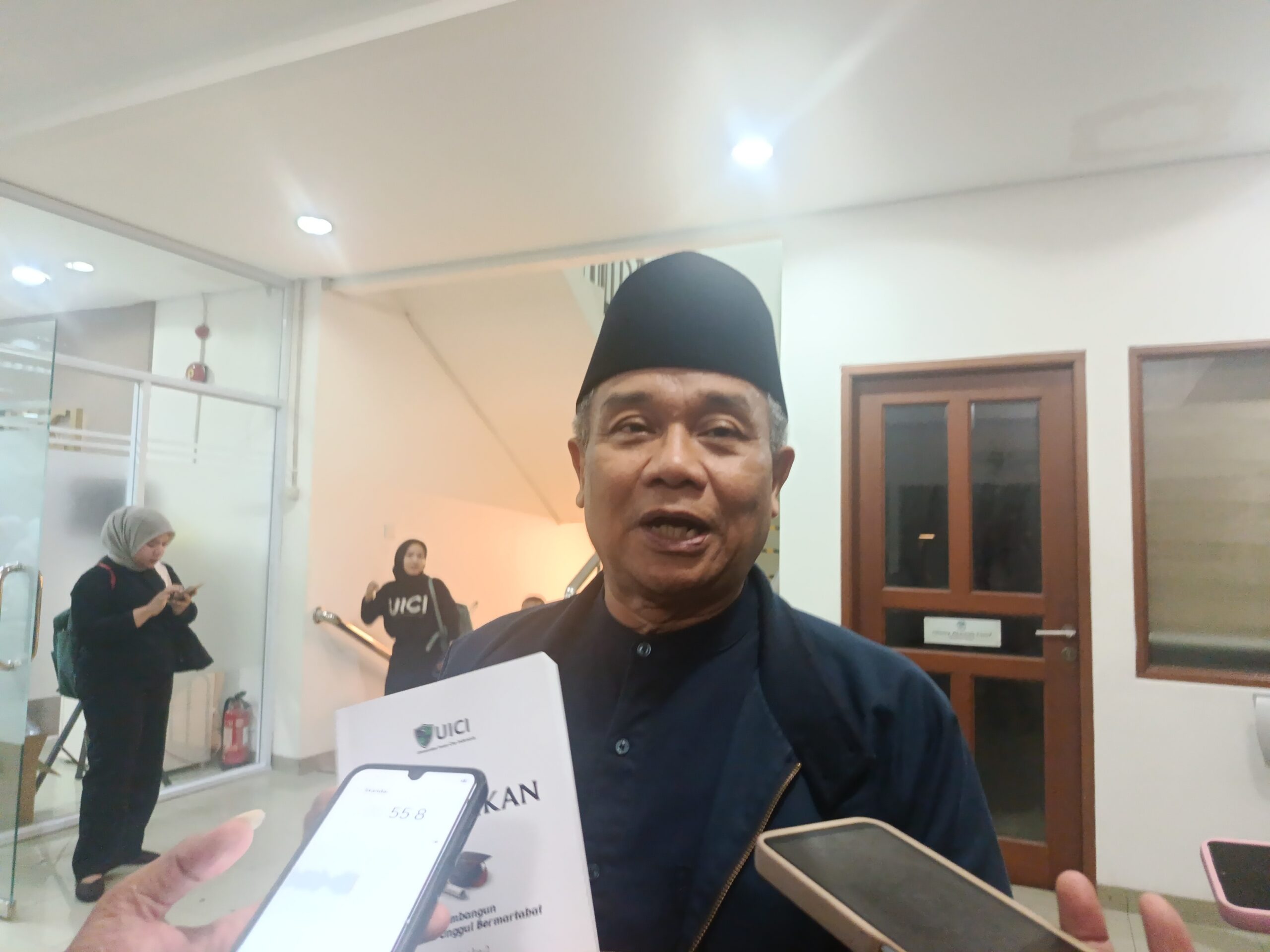Jakarta, 13 Oktober 2023.
Tanggal Pelaksanaan 16 – 17 Oktober 2023
Latar Belakang
Ketimpangan penguasaan tanah anat ini mencapai angka 0,68 (BPS, 2013), artinya terdapat 1% orang menguak 68% tanah di Indonesia.
Konsentrasi penguasaan dan monopoli tanah oleh pengusaha dan badan-badan usaha swasta maupun negara telah mengakibatkan ketimpangan, konflik agraria, kerusakan alam dan kemiskinan struktural yang akut dan meluas.
Sejak Joko Widodo menjadi Presiden (2015 2022), Konsorum Pembaruan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 2.710 konflik agraria, yang berdampak pada tanah masyarakat seluas 5,88 juta Ha dan terjadi di seluruh sektor agraria, perkebunan, kehutanan, pembangunan infrastruktur, pertambangan, Pesisir pulau-pulau kecil, properti, agribisnis dan fasilitas militer, termasuk proyek strategis nasional (PSN) dan pariwisata premium Angka tertinggi konflik agraria selama 10 tahun terakhir ini didominasi Oleh konsesi perkebunan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan eskalasi konflik agraria akibat PSN. Sedikitnya 1.615 orang dikriminalisasi (ditangkap hingga divonis), 38 ditembak dan 69 orang tewas karena mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya di wilayah-wilayah konflik agraria. Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) mencatat sejak 2017-2022 terjadi 301 kasus yang merampas 8,5 juta Ha wilayah adat dan mengkriminalisasi 672 jiwa warga Masyarakat Adat.
Tidaklah mengherankan, jumlah Petani kecil (gurem) dan Petani yang kehilangan tanah (landless peasants) serta menjadi korban konflik agraria semakin meningkat di Indonesia. Seolah tak cukup, Secara sistematis dan terstruktur juga terjadi peminggiran posisi dan peran Petani, Masyarakat Adat, Nelayan, Petambak dan Peternak rakyat sebagai produsen pangan nasional yang utama.
Situasi ini akibat konversi tanah pertanian ke non-pertanian yang semakin cepat dan meluas, dan model-model baru perampasan tanah demi kepentingan investasi perkebunan (sawit), proyek pembangunan infrastruktur, bisnis butan dan tambang serta pengadaan tanah untuk Bank Tanah.
Krisis agraria berimbas pada krisis lanjutan di sektor pertanian rakyat, yang pada akhirnya mengancam eksistensi petani dan pertanian keluarga di Indonesia.
Orientasi kebijakan pertanian pangan berbasis korporasi dan militer semakin memperparah krisis agraria multi dimensi, melalui Program Food Estate, Cetak Sawah Baru, Program Ketahanan Pangan, serta keran importasi pangan yang dibuka lebar hasil UU Cipta Kerja (UUCK).
Berdasarkan Data Sensus Pertanian 2013, ada 11,51 juta keluarga petani gurem, dan hanya dalam kurun waktu lima tahun (2013-2018), guremisasi kelas petani melonjak tajam menjadi 15,8 juta keluarga atau bertambah sekitar 4,29 juta keluarga (BPS, Survey Pertanian Antar Sensus, 2018). Fakta terbaru, sebanyak 72,19% petani merupakan petani gurem dimana 91,81% diantaranya adalah petani laki-laki dan 8,19% merupakan petani perempuan (BPS-Sintesis, 2021).
Komersialisasi agraria – SDA juga telah mengubah model-model produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat tapak. Hal ini berdampak lebih jauh pada hilangnya pengetahuan dan kekayaan tradisional, pergeseran peran penting petani, peladang, nelayan, petambak, peternak sebagai produsen pangan utama menjadi konsumen industri pertanian dan pangan, termasuk pupuk, benih, pestisida, dan bahkan produk pangan berbasis industrial Problem agraria struktural dan akut di atas disebabkan oleh sistem ekonomi-politik agraria yang semakin liberal dan kapitalistik, dimana prioritas tanah dan kekayaan alam sebesar-besar untuk kepentingan badan usaha skala besar. Ketidakadilan agraria ini berbanding terbalik dengan situasi agraria yang dihadapi Petani, Masyarakat Adat, Nelayan, Buruh, Perempuan dan Masyarakat Miskin di pedesaan maupun di perkotaan.
Secara khusus, orientasi ekonomi liberal dan kapitalistik meminggirkan aspek-aspek kehidupan yang fidak berorientasi pasar yang umumnya menjadi ranah perempuan sehingga turut menyebabkan eksklusi sosial-ekonomi-politik-budaya yang dialami mayoritas perempuan di tingkat tapak, dan secara sistemik menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas kedua yang tak terlihat.
Dampak lanjutan dari model pembangunan yang liberal dan kapitalistik tersebut telah mengakibatkan kerusakan alam, meningkatnya bencana ekologis dan konflik sosial. Di berbagai titik di Indonesia yerjadi banjir, longsor, kekeringan, kebakaran, abrasi dan kenaikan air laut.
Di sisi lain terjadi krisis pangan karena pencemaran lingkungan. WALHI mencatat bahwa bencana ekologis banjir terbesar yerjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat tahun 2021-2022. BNPB mencatat sebanyak 24.379 rumah terendam banjir, kurang lebih 112 ribu warga mengungsi, dan 15 orang meninggal dunia. Bahkan Presiden Jokowi sendiri mengatakan banjir tersebut merupakan yang terbesar dalam 50 tahun terakhir.
Bencana ekologis di atas terjadi sebagai hasil akumulasi dari berbagai pembukaan lahan yang dilakukan secara besar-besaran oleh kelompok korporasi dari tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, atas nama pembangunan yang berkedok ekonomi hijau, ekslasi perampasan ruang hidup masyarakat adat, petani, nelayan, dan masyarakat marginal lainnya semakin meningkat akibat proyek-proyek berlabel “hijau” yang mengikis kesuburan tanah, rakus air, laut dan sumber agraria lainnya.
Penanganan negara terhadap ketidakadilan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan Agraria – SDA menggunakan pendekatan keamanan dan menggeser konflik menjadi konflik sosial antar etnis, ras, agama, masyarakat lokal-pendatang, buruh perkebunan-Masyarakat Adat dan Petani, serta internal komunitas yang diadu-domba. Pendekatan keamanan dan politik pecah-belah semacam ini justru tidak menyentuh akar masalah ketimpangan dan konflik, bahkan semakin memicu munculnya konflik yang bersifat horizontal antar masyarakat.
Di sisi lain, generasi muda juga tereksklusi akibat orientasi ekonomi liberal dan kapitalistik tersebut. Pada masyarakat yang ruang hidupnya direbut, generasi mudanya menjadi kelompok yang tidak memiliki banyak pilihan penghidupan, sementara kekurangan modal dan ketiadaan sistem pendukung seperti pendidikan yang kontekstual serta ruang-ruang ekspresi dan partisipasi dalam kehidupan sosial, menjadi penghambat dalam mengembangkan potensinya semaksimal mungkin.
Hal ini tercermin dalam data Susenas BPS tahun 2021 yang menunjukkan lebih dari tiga juta populasi muda di rural tidak memiliki pekerjaan (Susenas BPS, 2021).
Hal ini tentu saja berlawanan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang ditargetkan pemerintah di mana generasi muda memainkan peran sentral dalam pencapaiannya
Wajah buruk realitas agraria di atas menjadi sebuah ironi dan paradoks, sebab di waktu bersamaan pemerintah tengah menjanjikan pelaksanaan Reforma Agraria (RA) seluas 9 juta hektar untuk rakyat.
Pada masa awal pemerintahan, agenda Reforma Agraria diharapkan akan dijalankan dengan tujuan utama mengikis ketimpangan penguasaan tanah yang tajam, menuntaskan akumulasi konflik agraria struktural, dan memulihkan dan mengakui hak-hak rakyat yang terampas.
Agenda ini juga diharapkan menjadi jalan bagi perwujudan kedaulatan pangan dan penguatan sentra ekonomi rakyat sehingga cita-cita keadilan sosial, kesejahteraan dan keadilan ekologis dapat dicapai.
Sayangnya pelaksanaan Reforma Agraris ala Jokowi gagal direalisasikan. Setelah hampir satu dekade pezam pemerintahan Jokowi berjalan, Reforma Agraria dilakukan secara menyimpang jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial-ekologis, yaitu prinsip yang mengedepankan kelompok rakyat yang selama ini dimarjinalkan dalam sistem ekonomi-politik agraria, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan alam di dalam Proses-proses pembangunan berbasis agraria-SDA.
Pemerintah juga mendorong kebijakan Perhutanan Sosial sebagai jalan Untuk memberikan akses kelola kepada masyaraksi yang tinggal di sekitar atau di dalam klaim kawasan hutan negara, serta memasukan skema Hutan Adat ke dalamnya.
Pemerintah juga menyediakan jalur lain melalui Desa Adat, Wilayah “Kelola” Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Alih-alih kebijakan yang bersifat memangkas hambatan-hambatan pelaksanaan Reforma Agraria Sejati dan semakin memperkuat posisi rakyat, justru berbagai regulasi yang bertujuan memfasilitasi investasi dan segelintir kelompok elit bisnis-elit politik semakin banyak diproduksi dan dihasilkan dengan proses yang begitu cepat serta mudah. Mulai dari revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU IKN, Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Sementara itu regulasi yang mengarah kepada keadilan sosial dan lingkungan tidak kunjung diselesaikan dan diimplementasikan, seperti TAP MPR IX/2001, UUPA 1960, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perpres Reforma Agraria dan RUU Masyarakat Adat.
Peraturan perundang-undangan pro-investasi dan kontra-Reforma Agraria seperti UU Cipta Kerja semakin mengukuhkan klaim sepihak Negara atas tanah dan kekayaan (dikenal dengan azas Domienverklaring), melanjutkan dualisme pertanahan di Indonesia menjadi klaim tanah dan kawasan hutan oleh negara, dan memperhebat proses-proses liberalisasi dan komersialisasi atas tanah dar kekayaan alam.
Tanah dan kekayaan alam diposisikan semata sebagai barang ekonomi dimana orientasi bisnis berbasis agraria-SDA semakin mendapatkan ruangnya di Tanah-Air. Akibatnya ketidakpastian hak atas tanah dan kerentanan tenurial rakyat semakin nyata.
Watak domienverklaring-kuasa sepihak dan mutlak negara atas tanah dan hutan—merupakan Permasalahan agraria struktural yang telah ada sejak zaman kolonial, sudah dihapus oleh UUPA, tetapi dihidupkan kembali di rezim otoritarian Orde Baru lewat UU sektoral, dan justru semakin diperkuat di masa Reformasi. Bukti termutakhir, watak tersebut terkandung kuat di dalam rumusan-rumusan UU Cipta Kerja dan UU IKN yang inkontitusional.
Sebagai manifestasinya, pemerintah kemudian menawarkan solusi palsu seperti: Bank Tanah dan hak pengelolaannya (HPL): Perhutanan Sosial yang bersifat mengukuhkan klaim sepihak kawasan hutan negara di atas desa, tanah pertanian dan wilayah adat, Skema Perkebunan Sosial dan Distribusi Manfaat yang ingin mengukuhkan klaim perkebunan negara di atas tanah-tanah masyarakat, Kebijakan keterlanjuran dan pengampunan bisnis ilegal di kawasan butan (Forest Amnesty), dan Perdagangan Karbon sama halnya di wilayah perkotaan, UU Cipta Kerja yang berwatak pro-investasi merancang penguatan posisi dan pemberian previledge atas tanah kepada para pemilik modal.
Kita telah menyaksikan tanah-tanah di kota dikuasai oleh konglomerasi properti yang membangun pusat-pusat kerajaan bisnis, dimana rakyat kecil dan masyarakat miskin kota hanya hidup di ruang-ruang sisa, seperti perkampungan kumuh dan bantaran kali. Cadangan aset tanah dan penguasaan tanah maha luas dalam genggaman para pemilik modal ini telah melahirkan ketimpangan agraria dan kemiskinan struktural yang akut di perkotaan.
Undang-undang Cipta Kerja yang menjanjikan penyediaan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan bagi rakyat kecil, seperti buruh dan kelompok marjinal di perkotaan nampaknya hanya menjadi mitos. Di tengah krisis agraria Yang dialami kelompok marjinal, resesi ekonomi dan pemutusan hubungan kerja (PHK) justru makin Menjalela di perkotaan.
Tantangan dan ancaman lain yang dihadapi gerakan masyarakat sipil adalah menyempitnya ruang publik (shrinking civic Space), yang terlihat dari aktivasi para pendengung pemerintah di dunia maya, maraknya pembubaran paksa diskusi-diskusi publik, stigmatisasi terbadap perjuangan masyarakat, kriminalisasi terhadap demonstran dan aktivis, penyadapan dan pembajakan digital, pembungkaman akademisi, hingga banyaknya pembela hak atas tanah, lingkungan dan HAM yang menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk.
Semua ini telah secara sistematis menambah lapisan-lapisan penghambat dan mempersempit partisipasi rakyat termasuk Masyarakat Adat, Petani, Nelayan, Perempuan, Generasi Muda, Buruh, Masyarakat Miskin di pedesaan dan perkotaan.
Seturuh krisis agraria – SDA dan kebebasan rakyat yang terjadi meoudiukkan kesalahan fundamental paradigma dan model-model pembangunan yang tidak sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Perubahan mendasar Untuk menjawab berbagai permasalahan hak-hak rakyat membutuhkan respon efektif dan aksi kolektif lintas gerakan rakyat.
Pergantian Kekuasaan yang akan datang adalah momentum penting agenda-agenda perubanan yang dilahirkan dari konsolidasi
rakyat. Untuk itulah Konferensi Tenurial 2023 yang mengusung tajuk “Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekologis melalui Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam” akan diselenggarakan oleh gerakan rakyat lintas sektor.
Konferensi ini penting juga ditempatkan sebagai konsolidasi modal sosial, ekonomi, budaya, politik dan pengetahuan rakyat yang akan menjadi dasar pembentukan kekuatan kolektif gerakan masyarakat sipil dalam menjawab berbagai tantangan struktural di atas dan di masa depan.
Tujuan Konferensi
Tujuan Umum: Menciptakan kondisi dan prasyarat yang memungkinkan terjadinya pelaksanaan Reforma Agraria Sejati dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang beradab sebagai jalan mewujudkan keadilan sosial-ekologis bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Tujuan Khusus:1. Membangun konsensus nasional tentang Reforma Agraria dan pengelolaan SDA yang berkeadilan sebagai agenda strategis dan tuntutan utama gerakan masyarakat sipil terhadap pembuat kebijakan dan penyelenggara pemerintahan ke depan;2. Membangun konsolidasi gerakan sosial yang lebih kuat dan luas di antara gerakan reforma agraria, gerakan masyarakat adat, gerakan nelayan, gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan perempuan, perkotaan, kelompok marginal dan gerakan sosial lainnya;3. Mengonsolidasikan aspirasi dari perempuan, kaum muda dan kelompok marjinal tentang keadilan agraria dan ekologis;4. Meningkatkan pengetahuan publik mengenai masalah agraria-SDA di pedesaan dan perkotaan dan5. Menyediakan pedoman bersama bagi gerakan masyarakat sipil dalam mewujudkan Reforma Agraria dan pengelolaan SDA yang berkeadilan.
Pasca-konferensi1. Memastikan hasil konferensi menjadi program kerja utama lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat local (desa dan/atau kampung);2. Memastikan hasil konferensi menjadi agenda yang memandu konsolidasi gerakan masyarakat sipil di tingkat regional dan nasional.
Mekanisme Konferensi Tenurial 2023Proses konferensi Tenure 2023 ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) agenda utama yaitu:1. Pra-konferensiPada pra-konferensi, isu, pengalaman, dan cerita keberhasilan di tingkat tapak akan ditangkap melalui Konferensi Regional untuk memperkuat dokumen konferensi yang telah disusun Tim Substansi. Konferensi Regional akan diselenggarakan di tujuh region dan diikuti oleh komunitas, organisasi rakyat, Oganisasi non-pemerintah, dan perguruan tinggi yang bekerja secara konsisten dan strategis dalam Isu-isu Hak Asasi Manusia dan tenurial di tingkat tapak.
Untuk setiap region, diwajibkan komposisi kepesertaan minimal 70% dari kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok marginal dan rentan lainnya.
Kegiatan ini akan diselenggarakan di Sumatera (Sumatera Utara), Kalimantan (Kalimantan Barat): Sulawesi (Sulawesi Selatan), Maluku dan pulau-pulau kecil (Maluku), Papua (Papua Induk), Jawa (Jawa Tengab), dan Bali-Nusa Tenggara (Bali).
Kegiatan lainnya yang menjadi rangkaian pra-konferensi dan dapat dikontribusikan anggota Koalisi Tenur maupun jejaring Masyarakat sipil baik di tingkat regional maupun nasional antara lain:
– Asia Learning EXChange
– Pameran– Podcast– Media briefing– Kompetisi foto dan/atau video pendek– Media trip– Webinar pra konferensi– Konsolidasi
2. Konferensi Nasional
Konferensi Nasional pada 10-12 Oktober mendatang akan menjadi ruang konfirmasi, dan pembangunan legitimasi atas substansi yang telah dibangun selama Pra Konferensi. Konferensi ini akan membahas pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dari aspek politik, kebijakan, krisis multidimensi, serta keberhasilan dan arah perbaikan ke depan.
Konferensi juga akan secara khusus membahas isu-isu agraria dan SDA yang berdampak kepada perempuan, pemuda, dan kelompok marginal dan rentan lainnya, serta agenda pembangunan yang berkonsekuensi pada konflik agraria di wilayah-wilayah khusus seperti Otorita, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus, Konferensi Nasional juga akan menjadi ruang konsolidasi gerakan masyarakat sipil lintas sektor (perani, buruh, masyarakat adat, nelayan, komunitas miskin kota dan CSO/NGO di luar Koalisi Tenur).
Hasil dari Konferensi Nasional adalah konsensus nasional dan strategi realisasi keadilan sosial-ekologis melalui pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, baik untuk masyarakat sipil maupun pemerintahan ke depan.

 Metro2 hari ago
Metro2 hari ago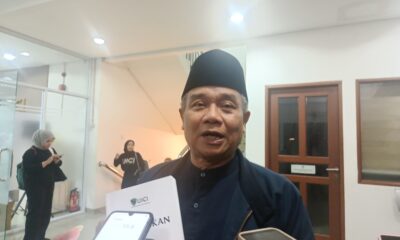
 Metro1 hari ago
Metro1 hari ago
 Metro2 hari ago
Metro2 hari ago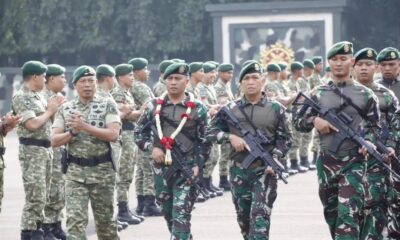
 TNI / Polri1 hari ago
TNI / Polri1 hari ago
 TNI / Polri3 hari ago
TNI / Polri3 hari ago
 TNI / Polri2 hari ago
TNI / Polri2 hari ago
 TNI / Polri21 jam ago
TNI / Polri21 jam ago
 TNI / Polri21 jam ago
TNI / Polri21 jam ago